Pencarian Arsip
Pusat Arsip dan Museum Ubaya memfasilitasi pencarian arsip melalui Portal Ubaya.
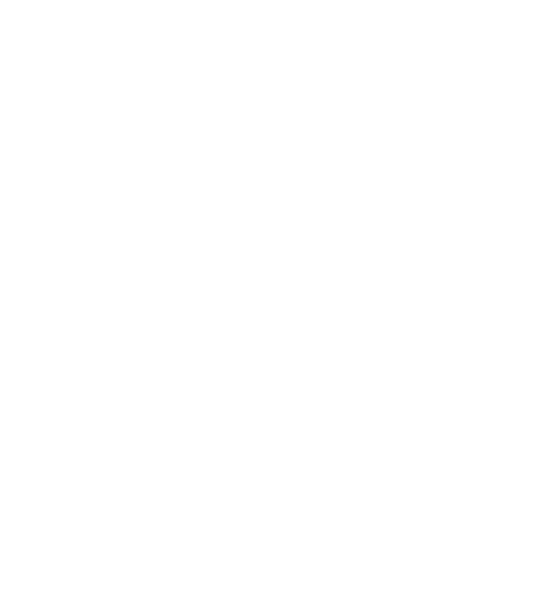
Kegiatan Orientasi untuk Mahasiswa Baru Universitas Surabaya (UBAYA) pada Tahun 1975 di Kampus UBAYA-NGAGEL, Jl. Ngagel Jaya Selatan No. 169
Gedung Perpustakaan UBAYA yang dibangun pada akhir kepemimpinan Prof. Mr.R. Boedi Soesetya, 1994
Kegiatan Orientasi untuk Mahasiswa Baru Universitas Surabaya (UBAYA) pada Tahun 1975 di Kampus UBAYA-NGAGEL, Jl. Ngagel Jaya Selatan No. 169
Kegiatan Orientasi untuk Mahasiswa Baru Universitas Surabaya (UBAYA) pada Tahun 1975 di Kampus UBAYA-NGAGEL, Jl. Ngagel Jaya Selatan No. 169
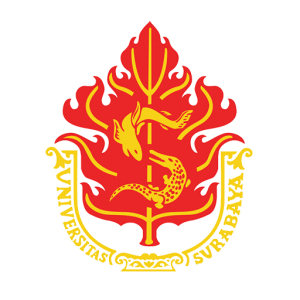


Senin - Jumat
08.15 - 16.30 WIB

Ketentuan layanan pusat arsip dan museum Universitas Surabaya dapat dibaca disini.

Universitas Surabaya - Kampus Ngagel
Jl. Ngagel Jaya Selatan 169 Surabaya
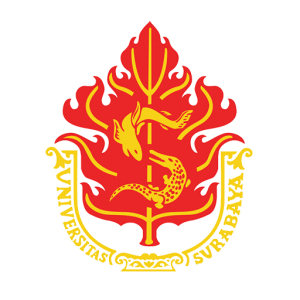
Pusat Arsip dan Museum Ubaya memfasilitasi pencarian arsip melalui Portal Ubaya.
Penambahan khasanah aset museum dilakukan dengan cara melalui hibah, sumbangan, tukar menukar dan beli.
Proses dan kerja dalam rangka perlindungan arsip terhadap kerusakan arsip atau unsur perusak dan restorasi/perbaikan bagian arsip yang rusak.







Your safety is our first priority. Entry to the UBAYA Museum is still free, but to help us ensure social distancing.
Learn More

User dapat mengakses informasi tentang benda-benda bersejarah melalui scan barcode saat berkunjung ke museum.
Learn More